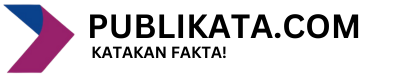Publikata.com – Pagi hari di Labuan Bajo adalah simfoni yang datang dari laut. Suara jangkar diangkat, deru mesin kapal dinyalakan, dan tiupan peluit kapten yang mengisyaratkan keberangkatan. Di pelabuhan dan dermaga-dermaga kecil yang menjulur ke Teluk Bajo, ratusan kapal phinisi berjajar laksana pasukan laut yang siap berlayar membawa para pelancong menuju pulau-pulau eksotis Padar, Rinca, Komodo, Kelor, dan puluhan gugusan surga lainnya di Nusa Tenggara Timur.
Labuan Bajo, kini, lebih dari sekadar nama kampung. Ia telah menjelma menjadi simbol kejayaan pariwisata bahari Indonesia. Kota kecil ini dikenal dunia sebagai “Kota Seribu Kapal Phinisi,” tempat di mana kemewahan layar dua tiang bersanding dengan langit biru dan air sejernih kristal. Tapi di balik layar indah itu, ada pertanyaan besar yang terus menggema, apakah kapal-kapal itu membawa kesejahteraan atau justru menenggelamkan yang lemah?
Kapal Phinisi, Warisan dan Komoditas
Phinisi bukan sekadar alat transportasi laut. Ia adalah warisan budaya yang lahir dari tangan-tangan pelaut Bugis dan Makassar, kapal layar kayu yang dahulu membawa rempah-rempah, kini membawa wisatawan kelas atas. Di Labuan Bajo, kapal-kapal ini tampil megah berinterior kayu berkualitas, berlayar putih mengembang, lengkap dengan kamar ber-AC, restoran terapung, bahkan jacuzzi.
Dalam sehari, ratusan kapal berlayar dari Labuan Bajo ke pulau-pulau di Taman Nasional Komodo, menjanjikan pengalaman “live on board” yang eksklusif. Pariwisata bahari pun meledak. Harga sewa satu kapal bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk paket beberapa hari. Operator kapal tumbuh bak jamur setelah hujan. Ekonomi lokal tampaknya menggeliat.
Tapi apakah benar kota ini makmur karena ribuan kapal itu? Kota yang Sibuk Tapi Tak Semua Tumbuh
Di balik gemerlap pelabuhan dan cerita tentang wisata mewah, kehidupan warga lokal berjalan di jalur yang berbeda. Banyak kapal dimiliki oleh investor dari luar daerah. Warga lokal lebih banyak menjadi anak buah kapal (ABK), koki, atau pemandu, dengan bayaran yang tidak selalu adil. Hanya segelintir yang benar-benar memiliki kapal sendiri.
Kota menjadi sibuk, harga tanah dan sewa tempat melonjak, dan banyak warga tergusur dari kampungnya sendiri. Sementara itu, kampung nelayan yang dahulu menjadi fondasi Labuan Bajo mulai kehilangan tempat secara harfiah dan simbolis.
Laut yang Terbebani
Dengan begitu banyak kapal beroperasi, ekosistem laut pun mulai terancam. Terumbu karang rusak oleh jangkar yang tidak terkendali. Sampah dari kapal menumpuk di permukaan laut dan pantai. Air limbah kapal kerap dibuang sembarangan, mencemari teluk yang dahulu bening.
Taman Nasional Komodo yang mestinya menjadi kawasan konservasi laut, justru menjadi zona paling padat lalu lintas wisata. Ironi ini begitu terasa: kawasan konservasi yang dikepung oleh industri pariwisata massal.
Antara Romantisme dan Kenyataan
Kapal phinisi memang cantik. Ia melambangkan kebanggaan akan warisan bahari Indonesia. Tapi saat ribuan kapal itu datang tanpa tata kelola yang jelas, keindahan bisa menjadi ancaman. Kemewahan bisa menyingkirkan kesederhanaan. Dan romantisme laut bisa menutupi kenyataan bahwa tidak semua orang di Labuan Bajo ikut menikmati kekayaan yang mereka bantu ciptakan.
Penulis : Alexandro Hatol
Editor : Jupir